

Saat ini, teks Al-Quran dapat dikatakan telah final, semua umat Islam, mulai dari kaum Sunni, Syiah, dan lainnya sepakat untuk menggunakan Al-Quran versi final yang saat ini beredar. Kita juga mengimani kekitabsucian Al-Quran yang diturunkan sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Meskipun begitu, Al-Quran sebagai bundelan kitab saja tidak akan memberi manfaat yang signifikan kehidupan manusia itu secara otomatis. Manusialah yang harus berinisiatif melakukan interaksi dan dialog dengan Al-Quran untuk mengali keteladanan yang baik yang ada di dalamnya.
Di dunia dengan kebudayaan lisan yang dominan, ada beberapa kritik terhadap Al-Quran yang telah menjadi kebudayaan tulisan ini. Misalnya saja pada Kerajaan Mali Kuno di Afrika yang berkembang melalui tradisi lisan. Melalui griot, syair puisi khas Mali yang berisi pesan turun temurun, banyak ungkapan yang memprotes ‘matinya’ ajaran yang mulai berhenti pada tulisan. Dalam pandangan bangsa Mali, penyampaian ajaran melalui tulisan dipandang lebih rendah dibandingkan melalui ajaran lisan dan kisah yang dirasakan lebih ‘hidup’.

Sundiata Mansa adalah pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Mali pada abad ke-13. Dia memeluk Islam sambil tetap mengembangkan agama lokal di kerajaannya. Melalui epiknya, dengan sinis ia mengkritik budaya yang terpaku pada teks mati : di dalam tulisan tidak ada kemampuan merasakan masa lampau dan tidak ada kehangatan suara manusia.
Orang lain memakai tulisan untuk merekam masa lampau, tetapi penemuan ini telah membunuh kemampuan ingatan mereka.
Mereka tidak lagi merasakan masa lampau, sebab tulisan tidak lagi mengandung kehangatan suara manusia.
***
Di Indonesia, proses dialog dengan Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara khas Indonesia. Pada beberapa cara, Al-Quran yang dijadikan sebagai objek ritual, misalnya secara tradisional dengan menjadikan tulisan Al-Quran sebagai azimat atau hal lain yang berbau mistis. Beberapa dukun punya ayat favorit untuk para pelanggan setia mereka. Secara modern, Al-Quran juga digunakan sebagai simbol ritual misalnya pada proses pengambilan sumpah jabatan atau kesaksian di pengadilan.
Masyarakat Indonesia juga memiliki budaya pengajian yang melakukan pelisanan kembali Al-Quran. Umumnya, pelisanan Al-Quran dilakukan sesuai kaidah bacaan Arab yang baik meskipun arti dan makna tulisan ini jarang sekali dimengerti. Keindahan alunan orang mengaji tentunya menjadi aspek tersendiri dalam dialog dengan Al-Quran. Tetapi saya tidak bermaksud membahas dialog jenis yang ini.

Kadang-kadang timbul pertanyaan mengenai bagaimana cara berdialog kembali dengan Al-Quran seperti masa turunnya dahulu. Mengkhatamkan Al-Quran dalam arti melagukan bacaan dari Al-Fatihah hingga ke An-Nas jelas belum merupakan definisi dialog yang tepat untuk saya. Lebih penting dari itu, kita seharusnya melihat bagaimana sejarahnya ketika ayat demi ayat turun? Kemudian, pada latar belakang budaya apa proses penurunan ayat demi ayat ini terjadi? Penelusuran ini membuat kita menjadi tidak memandang Al-Quran sebatas tulisan asing (Arab) yang makblug menjadi hidangan fast food yang siap disantap. Ada proses pengertian dan akulturasi antara ajaran Al-Quran ini dengan realitas kehidupan kita yang tidak selalu sama dengan waktu ayat demi ayat ini diturunkan.
Apalagi kalau nanti kita berkesempatan masuk ke khasanah tafsir Al-Quran yang beraneka ragam, mulai dari yang fundamentalis ala Sayyid Qutb, yang rasionalis ala Ar-Razi, yang tradisionalis ala Ibnu Katsir, atau yang modernis ala Muhammad Abduh. Tidak tertutup kemungkinan juga, kalau kita mau membuat tafsir Al-Quran ala penduduk Jakarta misalnya. Saya pikir, itu sah-sah saja. Tindakan semacam ini moga-moga membuat kita bisa memahami Al-Quran beyond the text dan kembali lagi, memahaminya berdasarkan realitas kehidupan kita yang terus berubah.
Ini misalnya saja lho, tapi saya mau sedikit berandai-andai kalau saja Al-Quran diturunkan pada waktu sedikit lebih lama, mungkin kewajiban perkawinan satu suami hanya dengan satu istri saja (monogami) dan pelarangan perbudakan dapat menjadi bagian dari ayat-ayat Al-Quran. Memang pada abad ke-7 di dunia Arab, kesetaraan gender dan ras masih merupakan suatu hal yang aneh. Perdagangan budak dilakukan secara umum di pasar-pasar, wanita diperlakukan sebagai aset kebendaan yang sah-sah saja diwariskan atau dipindahtangankan.
Sebelum turunnya Al-Quran, budaya Arab menganggap sebuah kewajaran bagi pria untuk memperistri banyak wanita dan memiliki selir bahkan lebih banyak lagi. Secara final, Al-Quran sendiri berhasil melakukan perubahan sosial ketika itu agar pria memperistri maksimal empat wanita saja, itu pun diembel-embeli dengan prasyarat yang tidak mudah: kalau sang pria merasa adil. Berdasarkan hal ini, saya melihat semangat kesetaraan gender dan ras ini menjadi agenda yang cukup penting dalam Al-Quran, meskipun belum terselesaikan dalam proses keberangsurannya.
Lebih jauh, kalau kita ekstrapolasikan, perubahan sosial yang menjadi misi Al-Quran belumlah selesai, bahkan mungkin tidak akan pernah selesai. Nilai universal yang berada di dalamnya perlu kita pahami dengan baik. Al-Quran sebagai sumber hukum merupakan sumber inspirasi yang tidak pernah habis. Sebagai implementasi semangat perubahan sosialnya, hukum-hukum jurisprudensi (fiqh) dan implementasi sosial misalnya, perlu selalu kita formulasikan ulang sesuai dengan realitas dan latar belakang budaya yang kita miliki.
Kita bisa lihat sampai saat ini update hukum-hukum ini masih menjadi pe er yang belum terselesaikan di kalangan Islam. Penganiayaan seksual TKW di Arab Saudi tidak dianggap sebagai pemerkosaan karena wanita masih dianggap sebagai aset kebendaan. Harem-harem masih bertebaran di dunia Islam Timur Tengah. Ayat-ayat Al-Quran masih menjadi justifikasi poligami di Indonesia. Wanita tidak bebas berkeliaran di malam hari karena penerapan syariah di beberapa otonomi daerah yang menerapkan ‘syariat Islam.’ Dan masih banyak penerapan sosial lainnya yang malah menghalangi aktivitas yang membebaskan dan mencerahkan.
Kesepakatan ulama di masa lalu sepertinya perlu terus kita kaji untuk mendapatkan semangat perubahan sosial yang diusung oleh Al-Quran. Isu kesetaraan gender saja misalnya, mencakup kajian panjang pada aspek jurisprudensi yang tidak sedikit: hierarki wanita dalam keluarga, pembagian harta warisan, pembebasan aktivitas sosial wanita, kepemimpinan wanita, dan hal lain.
Well, ada yang bilang sikap ini merupakan penafsiran yang kontekstual. Ada juga yang bilang itu kompromi agama dengan realitas. Dan ada orang yang bilang itu bid’ah. Ragam pendapat ini sah-sah saja, asal disampaikan dengan santun. Tapi kemarin ini, terus terang saya sempat ‘ditampar’ oleh pernyataan sinis Sundiata yang lain :
Para Nabi tidak menulis, dan karena itu sabda mereka menjadi hidup. Betapa sia-sia ajaran yang terbungkus dalam buku yang dungu!
(Sundiata : An Epic of Old Mali, D.T. Niane)







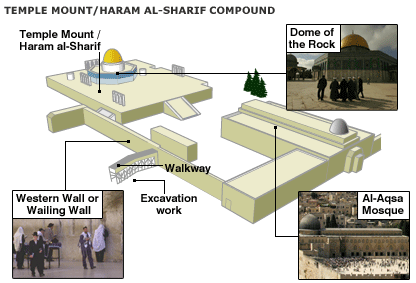





.jpg)






