Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Ho-lopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama!
(Soekarno)
“KORUPSI” adalah trending topic di Indonesia pada beberapa tahun belakangan. Mulai dari media konvensional macam koran, televisi, radio, hingga media sosial macam Twitter dan Facebook membanjiri kita dengan berbagai berita korupsi. Terus terang saya mulai bosan dengan omongan ‘pakar’ tentang korupsi. Meskipun saya sepakat bahwa korupsi merupakan hal yang salah dan patut diberantas, tapi apa korupsi benar-benar bisa hilang dari Indonesia?
Karena, kalau boleh jujur, korupsi sangat dekat dengan realita kehidupan kita. Untuk mengurus KTP, kita memberikan uang lelah pada Petugas Kelurahan sebagai ganti ‘kerepotannya’ (tanpa diminta). Ketika ditilang, kita menyelipkan lima puluh ribu rupiah saat menunjukkan SIM dan STNK kepada Polantas. Kita juga setengah bangga memajang kiriman parsel lebaran dari supplier perusahaan kita. Dalam hati kita berkata, “Hey, ini bukan korupsi, tapi budaya ramah tamah, kekeluargaan, gotong royong khas Indonesia. Lagi pula, kalau pemberian dilakukan dengan ikhlas maka akan diterima di sisi-Nya.”
Menjadi kontradiksi saat mengikuti dan mengomentari media massa dan media sosial, kita mengutuk keras perilaku korupsi aparat pemerintah yang menerima kick-back dari rekanan tender, para anggota DPR yang memperjualbelikan pasal, para polisi, jaksa, dan hakim makelar kasus, para devil advocate pembela klien koruptor, dan para pengusaha yang tertangkap tangan oleh KPK membawa uang sogokan tunai. Mereka ‘oknum’ koruptor adalah penjahat dan harus dihukum seberat-beratnya. Sedangkan, kita sendiri adalah korban atas ulah mereka.
Apakah mengutuk koruptor sambil menonton acara Indonesian Lawyer Club, sementara tetap memberikan uang lelah bagi petugas kelurahan bisa dikatakan sebagai sikap hipokrit alias munafik? Ah, terlalu kasar kedengarannya bagi bangsa Indonesia yang halus tutur kata budi bahasanya ini. Tapi jangan khawatir, beberapa ahli neurosains memang berteori bahwa kemunafikan merupakan sifat yang alami pada manusia.
Robert Kurzban, seorang ahli psikologi evolusi dari Princeton, dalam bukunya yang menarik, “Why Everyone (Else) Is a Hypocrite: Evolution and the Modular Mind” berpendapat bahwa evolusi manusia membuat pikirannya menjadi sangat canggih dan kompleks. Karena kompleksitasnya, pikiran manusia terdiri dari berbagai modul yang tidak koheren satu sama lain. Inkoherensi modul-modul pikiran inilah yang menjelaskan mengapa sikap munafik menjadi sesuatu yang tertanam dalam pikiran manusia.
Sementara di satu sisi moralitas menjadi modul panduan supaya kita tidak melakukan tindakan tidak bermoral (termasuk korupsi), di sisi lain modul pikiran lain dapat memerintahkan kita untuk mengambil keuntungan di atas kerugian orang lain. Masing-masing modul pikiran ini tanpa disadari tidak bertalian logis satu dengan lainnya, bahkan bisa saling bertentangan. Apa yang terlihat dari luar adalah ketidaksinkronan antara sikap dan perbuatan. Kesimpulan Kurzban, sifat munafik pada dasarnya kompetisi yang secara alamiah terjadi pada level pikiran. Hasilnya, standar moral memang membuat kita memenuhi time-line twitter dengan cercaan terhadap koruptor, tapi kita tetap menerima legowo ‘oleh-oleh’ dari para supplier kita.
Dari kacamata evolusi perilaku, tindakan koruptif malah menjadi rasional apabila dilakukan ‘berjamaah’. Ketika banyak orang lain melakukan korupsi dan mendapatkan keuntungan dari tindakan ini, menjadi orang yang tetap jujur malah menjadi pilihan yang tidak rasional, bahkan tidak menguntungkan. Hal ini menyebabkan penurunan frekuensi perilaku jujur pada lingkungan koruptif. Dari sudut pandang evolusi, perilaku jujur menjadi tidak fit dan sintas dalam lingkungan koruptif. Pendeknya, dari perspektif evolusi perilaku, kebiasaan korupsi dapat berkembang biak sangat cepat dibandingkan sifat jujur apabila telah mencapai massa kritis tertentu.
Sudut pandang evolusi perilaku terhadap korupsi ini menjelaskan bagaimana budaya sekitar dapat mempengaruhi tingkat korupsi. Setiap tahun Transparency International merilis Corruption Perception Index (CPI) yang merupakan penilaian tingkat korupsi di sektor publik setiap negara. Tahun 2010, Denmark, Selandia Baru, dan Singapura memiliki nilai index tertinggi (terbaik), yaitu sebesar 9,3. Sedangkan negara dengan index persepsi korupsi terendah (terburuk) adalah Somalia (1,1), Burma (1,4), dan Afganistan (1,4). Indonesia sendiri memiliki nilai indeks persepsi korupsi 2,8.
Bagaimana hubungan antara index persepsi korupsi dengan perilaku korupsi di masyarakat sehari-hari ini? Abigail Barr, seorang ekonom Oxford, meneliti sekelompok mahasiswa Oxford dari berbagai negara tentang seberapa mungkin mereka menyogok petugas pelayanan umum di Inggris untuk dapat keuntungan lebih. Kesimpulannya, ternyata probabilitas mahasiswa sarjana mau menyogok demi keuntungan lebih memiliki korelasi dengan index persepsi korupsi asal negaranya. Berdasarkan kesimpulan ini, orang Denmark, Selandia Baru, dan Singapura cenderung untuk tidak menyogok untuk mendapatkan keuntungan dibandingkan orang Somalia, Birma, dan Afganistan, juga termasuk Indonesia.
Di New York, Raymond Fishman dan Edward Miguel melakukan penelitian sejenis terhadap para diplomat berbagai negara untuk PBB. Sebelum tahun 2002, kekebalan diplomatik melindungi diplomat PBB dari denda pelanggaran parkir di kota New York. Hal ini membuat faktor penegakan hukum tidak dapat mengontrol perilaku koruptif dan menyisakan hanya norma budaya untuk menangkal korupsi. Ternyata, penelitian Fishman dan Miguel juga memberikan kesimpulan yang sama dengan penelitian Barr.
Hasilnya, para diplomat Denmark tidak melakukan pelanggaran parkir sama sekali, Selandia Baru memiliki 0,1 pelanggaran/diplomat, dan Singapura memiliki 3,6 pelanggaran/diplomat. Tidak ada data untuk tiga negara dengan indeks persepsi korupsi terburuk, tetapi Indonesia sendiri memiliki 36,5 pelanggaran/diplomat. Setelah tahun 2002, kekebalan diplomatik terhadap denda parkir ini dihilangkan dan pada tahun 2011 ini, hutang denda akibat pelanggaran parkir para diplomat Indonesia untuk PBB di New York sempat menjadi terbesar ke-3, sebesar 750 ribu dollar alias 6,7 miliar rupiah!
***
Apakah wajar kita menolak pemberian orang yang bermaksud ramah tamah? Seorang teman mengatakan bahwa petugas badan antikorupsi menolak minuman air putih saat berkunjung ke tempatnya. Sopankah perilaku ini di negara dengan budaya konformitas dan kohesi sosial yang tinggi seperti Indonesia? Masa menyajikan air putih saja saja dibilang menawarkan korupsi?
Saya punya teman seorang Amerika. Meskipun telah tinggal belasan tahun di Indonesia, ia tidak bisa memahami perilaku orang Indonesia. Pada minggu pertama kedatangannya di Indonesia, mobil yang ia tumpangi ditilang polisi. Saat supirnya akan memberikan uang ‘titip sidang’ kepada Polantas, ia kaget dan mencegahnya. Ia minta polisi itu tetap menilang supir mobilnya.
Dalam diskusi beberapa bulan lalu, teman Amerika ini mengklaim tidak pernah melakukan kegiatan sogok sedikitpun di Indonesia selama belasan tahun di Indonesia. Sebuah klaim yang terus terang sulit saya percayai. Ia berargumen tanpa maksud menghina, “’Kekeluargaan’ is a slippery slope. Once you slip in it, you will race to the bottom.”
Nah lho.. Saya jadi bingung: apa pemberantasan korupsi berarti melunturkan budaya khas Indonesia?
Inspirasi:
The underhand ape: Why corruption is normal
Corruption and culture: An experimental analysis
Corruption Perception Index Result 2010
Why Everyone (Else) Is a Hypocrite: Evolution and the Modular Mind
Corruption, Norms, and Legal Enforcement: Evidence from Diplomatic Parking Tickets






 Siapa yang belum menonton film “Sang Pencerah” karya Hanung Bramantyo? Film ini menggambarkan sebuah versi kehidupan KH. Ahmad Dahlan, sang pendiri organisasi Muhamadiyyah. Bagi yang belum, sila menyempatkan diri pergi ke bioskop untuk menonton sebelum film ini habis. Perkiraan saya, film ini akan usai tayang di layar lebar dalam satu dua minggu dan mulai dipasarkan lewat media DVD atau VCD.
Siapa yang belum menonton film “Sang Pencerah” karya Hanung Bramantyo? Film ini menggambarkan sebuah versi kehidupan KH. Ahmad Dahlan, sang pendiri organisasi Muhamadiyyah. Bagi yang belum, sila menyempatkan diri pergi ke bioskop untuk menonton sebelum film ini habis. Perkiraan saya, film ini akan usai tayang di layar lebar dalam satu dua minggu dan mulai dipasarkan lewat media DVD atau VCD.









![kuilindia155_thumb3[6] kuilindia155_thumb3[6]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7smUwaFjKvrNq04a2IqOyKgu1s1N4UF12-inOH9xE_87S0ShWJ2g-eOeyMyIoo3C-v_KDvwaarHNrWSK6jKiYFyffITfJ9Q8Xrw73rubEq4PJvcz51TTUxCjZ3xrPNEYh6n-D/?imgmax=800)
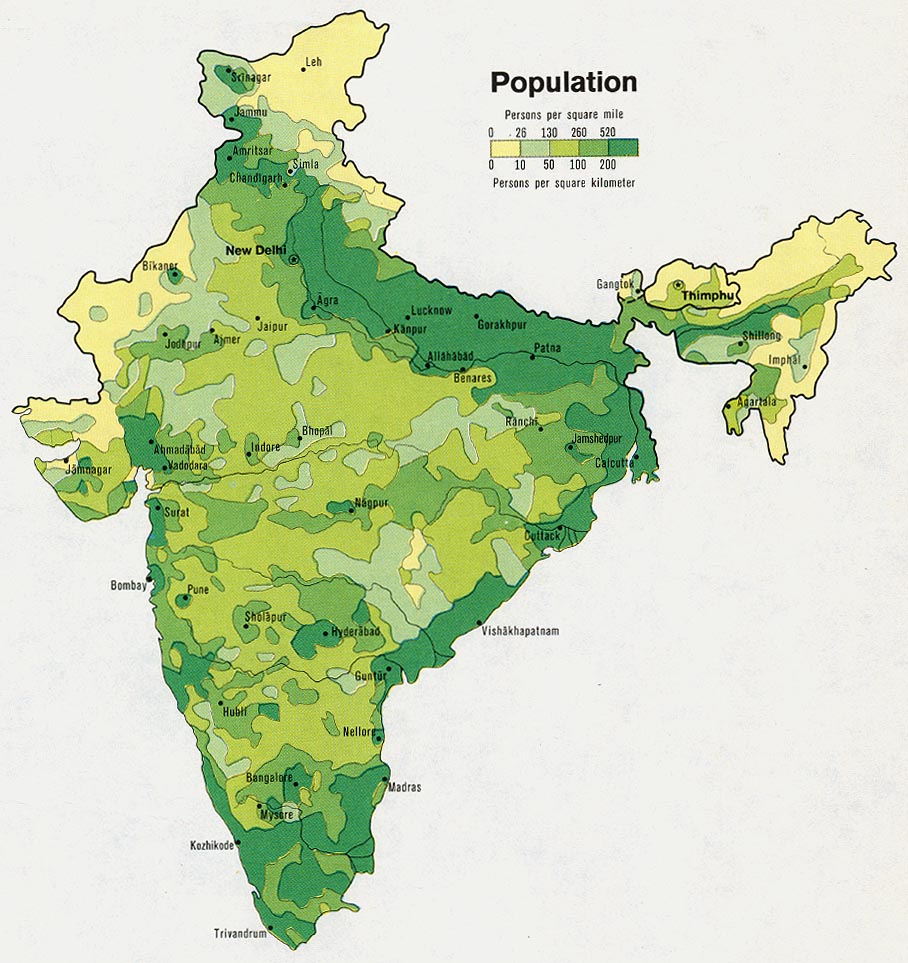 Kalau boleh jujur, peluang saya untuk secara sukarela kembali mengunjungi India lagi bisa dikatakan sangat rendah. Atau mungkin saya perkecil lagi scope-nya, dari luasnya negara India menjadi kota Delhi saja lah. Pengurangan ini saya lakukan dalam rangka mencegah stereotyping yang lagi-lagi saya lakukan tanpa sengaja di luar sadar.
Kalau boleh jujur, peluang saya untuk secara sukarela kembali mengunjungi India lagi bisa dikatakan sangat rendah. Atau mungkin saya perkecil lagi scope-nya, dari luasnya negara India menjadi kota Delhi saja lah. Pengurangan ini saya lakukan dalam rangka mencegah stereotyping yang lagi-lagi saya lakukan tanpa sengaja di luar sadar.




